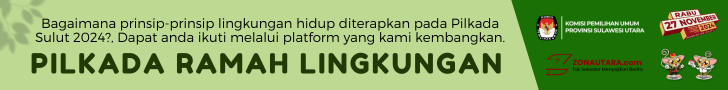MANADO, ZONAUTARA.com – Institut Seni Budaya Independen Manado (ISBIMA) yang menggawangi Pentas Sastra 2017 dilaksanakan oleh Balai Bahasa Sulawesi Utara (Sulut) berhasil menghadirkan sebuah pertunjukan yang menarik. Selain puisi-puisi yang dibawakan dengan konsep variatif, Achi Breyvi Talanggai yang menyutradarai jadwal Pentas Sastra 2017 kali ini, membuat penonton terhipnotis dengan garapan monolog ‘Tumbal Itu Belum Mati’, sebuah naskah yang mengangkat kisah Wijhi Tukul yang hilang di akhir rezim orde baru.
Ketua Umum Dewan Kesenian Daerah Sulut Kamajaya Al Katuuk yang hadir dalam momentum tersebut memberikan apresiasi yang konstruktif. Menurutnya, dari sudut pandang seni sebagai sebuah media pesan, di pentas kali ini, Achi lumayan berhasil.
“Indikatornya? Kata-kata menjadi kembali disadari: penting. Kata-kata akan menentukan nasib seseorang. Maka, memilih kata-kata dalam hidup ini, akan menentukan seperti apa hidup kita jadinya. Terutama kalau cara menonton pentas Achi dimulai dan dipusatkan pada penampilan terakhir, yakni monolog ‘Tumbal Itu Belum Mati’,” kata seniman gaek ini.
Untuk monolog ini, lanjutnya, sejak dari pemberitahuan di media, terutama yang diikuti di Facebook sampai saat pentas dihelat, jelas pemirsa digiring untuk menyiapkan diri bahwa yang dimaksud tumbal, tidak lain dan tidak bukan adalah Wijhi Tukul, seorang penyair protes yang diduga diculik, yang puisi-puisinya padat-melesat dengan kata-kata protes terhadap pemerintah batil waktu itu dan saat kapan saja, sejauh serupa tabiatnya.
“Pada pentas kali ini, Achi betul-betul menampilkan Marcelino R Silouw sebagai pemonolog mengandalkan satu modal, yaitu akting. Untuk daya tahan, dan keasyikan dalam hal beraksi panggung, saya pikir berhasil. Dalam ruang yang terkesan sumpek, sumir, sempit dan sungguh terbatas, Wijhi Thukul betul-betul hadir sebagaimana banyak diimajikan. Keberhasilan tersebut jelas, karena Achi mampu memadukan keberadaan Wijhi yang tak jelas, kisah publiknya apakah sudah mati atau masih hidup, dengan kemampuan pemeran yang bermain lugas sebagai pemikat di panggung,” urai Kamajaya.
Dijelaskannya lagi, teror terhadap Wijhi sebagaimana dimaklumi juga adalah teror massal terhadap akal sehat dan yang memperjuangkannya, tentu. Secara pribadi, respensi dan resepsi imajinya juga terbangkitkan.
Tentang Pentas Sastra 2017 ini, Kamajaya mengatakan bahwa sebagai sebuah pementasan standar, upaya Balai Bahasa Sulut, yang menyiapkan panggung dan uang pengganti produksi pantas dicatat.
“Program yang sudah beberapa tahun dijalankan ini jelas bermanfaat. Apalagi pelibatannya bersifat representasi dari berbagai sanggar, grup atau komunitas. Andai saja, tata ruang, seperti pendingin mulus dan kedisiplinan teman dalam menjaganya juga tulus, seperti tidak merokok dalam ruang, pasti akan jadi oase kreativitas, apalagi sarana serupa yang disiapkan pemerintah daerah, baik kota Manado maupun Provinsi Sulut, yang seperti biasa, luput dan abai,” ujarnya.
Maka beranalog dengan pentas ISBIMA kali ini, Kamajaya mengatakan bahwa kita sadar bahwa jika kata-kata tetap hidup, itu berarti bahwa kesadaran untuk mengambil peran dalam membina kewarasan melalui kesenian juga hidup. Seni berarti, karena kehadirannya membuat hidup bermakna.
Sementara itu, Jeffry Luntungan, sineas asal Sulut, mengungkapkan rasa senangnya bisa hadir dalam Pentas Sastra 2013 yang kedua ini.
“Banyak hal yang saya dapatkan di sini. Hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan, bisa ditemukan dalam garapan Achi kali ini,” ujar Jeffry.
Artikel kritik Achi bisa pula dibaca di: Mengulas Pertunjukkan Monolog Karina J. Hidayat, Teror Yang Impresif
Editor: Ronny A. Buol