SITARO, ZONAUTARA.COM-Dampak perubahan iklim berpotensi mengganggu stabilitas ketersediaan pangan, apalagi ditambah dengan produksi kelapa sawit bakal dibagi dengan sumber energi Biodiesel. Bagi sejumlah daerah penghasil akan cenderung lebih banyak stok, tapi bagaimana dengan kepulauan yang hanya bergantung pasokan dari luar. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) misalnya.
Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Sitaro, Joi E B. Oroh saat ditemui dalam launching gerakan tanam cabai di Kampung Beong, Kecamatan Siau Tengah menyampaikan ada upaya memutus ketergantungan pangan dari luar daerah.
Kepulauan Sitaro, kata dia, hingga saat ini untuk kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, bumbu dapur semuanya di angkut dari luar daerah, dengan kapal laut karena bukan daerah penghasil.
“Karena itu, kita akan mulai dengan menyeruhkan setiap warga untuk memanfaatkan lahan tidur atau pekarangan rumah, supaya hasilnya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga,” ucap Oroh.
Meski begitu kata Oroh, pemerintah berupaya dimulai dari Dinas Pangan dan Pertanian Sitaro yang membuka lahan demonstrasi plot atau lahan percontohan untuk tanaman cabai yang bisa dimanfaatkan warga untuk belajar menanam.
“Sudah dimulai lewat Dinas Pangan dan Pertanian,” kata dia.
Data produksi beras yang disampaikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada acara diskusi daring bertajuk, ‘Bahan Pokok Mahal: Pentingnya Keberlanjutan Pangan di Tengah Krisis Iklim,’ Selasa, 5 Maret 2024, disebutkan bahwa prediksi produksi total beras periode Januari-April 2024 mencapai 10,70 juta ton. Sedangkan produksi total beras tahun 2023 pada periode yang sama mencapai 12,98 juta ton. Artinya, produksi beras tahun ini (2024) lebih rendah 2,28 juta ton atau 17,57 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2023.
Adapun rincian produksi beras pada tahun 2024 mencapai 0,86 juta ton (Januari), 1,38 juta ton (Februari), 3,54 juta ton (Maret), dan 4,92 juta ton (April). Sedangkan pada tahun 2023, beras yang diproduksi adalah 1,34 juta ton (Januari), 2,85 juta ton (Februari), 5,13 juta ton (Maret), dan 3,66 juta ton (April).
“Jadi, volume produksi beras dari Januari hingga Maret 2024 diprediksi lebih rendah dibanding produksi beras pada dua atau tiga tahun lalu. Sehingga, kondisi ini merupakan musim paceklik yang luar biasa,” ujar Dr. Ir. Budi Waryanto, M.Si, – Plt. Direktur Ketersediaan Bapanas.
Berkurangnya produksi beras tidak terlepas dari cuaca ekstrem yang terjadi sepanjang tahun 2023. Vice Chair Working Group I, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) & Profesor Meteorologi dan Klimatologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Edvin Aldrian, mengatakan tahun 2023 merupakan tahun terpanas dengan kenaikan suhu global hingga 1,52 derajat Celcius. Hingga Maret 2023 tercatat kenaikan suhu ini melebihi batas yang ditetapkan pada Perjanjian Paris yaitu 1,5 derajat Celcius.
Menurut laporan IPCC, tambahnya, tahun 2030 kenaikan suhu bumi diperkirakan akan naik lebih cepat dari beberapa prediksi sebelumnya. Misalnya, pada tahun 2019 telah diperkirakan kenaikan suhu akan tembus beberapa derajat pada tahun 2052. Namun, pada temuan tahun 2020 suhu bumi diperkirakan akan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2042 atau 10 tahun lebih cepat dari prediksi awal.
“Suhu di bumi sudah melebihi 1,5 derajat celcius sepanjang dua belas bulan, Januari sampai Desember 2023. Kondisi ini terjadi 10 tahun lebih cepat dari prediksi sebelumya,” ungkapnya.
Dalam diskusi yang sama, Supari, Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan bahwa El Niño yang terjadi pada tahun 2023 merupakan kategori El Niño Moderat dengan indeks anomali suhu muka laut di Pasifik tengah mencapai nilai 2,0 pada Desember 2023.
Menurutnya dampak El Niño luar biasa terutama pada bulan Agustus hingga Oktober yang ditandai curah hujan yang sangat rendah terjadi di beberapa wilayah, bahkan kondisi tanpa hujan paling tinggi selama 222 hari tidak ada hujan di Lombok, NTB.
“Sementara itu untuk kondisi tanpa hujan lebih dari dua bulan terjadi di wilayah mulai dari Sumatera bagian Selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah dan Selatan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Papua, sehingga dapat dipahami banyak daerah yang mengalami kondisi produksi pangan yang tidak maksimal,” katanya.
Pemerintah dalam hal ini Bapanas telah melakukan beberapa langkah untuk menjaga ketersediaan pangan yaitu dengan menyediakan 2,4 juta ton setiap tahunnya, melakukan bantuan pangan untuk 22 juta masyarakat yang rawan pangan, melakukan stabilisasi pasokan dan harga untuk retail modern serta melakukan sinergi dengan pemerintah daerah melalui program gerai pangan murah di bawah program Kementerian Dalam Negeri untuk mengendalikan inflasi di daerah.
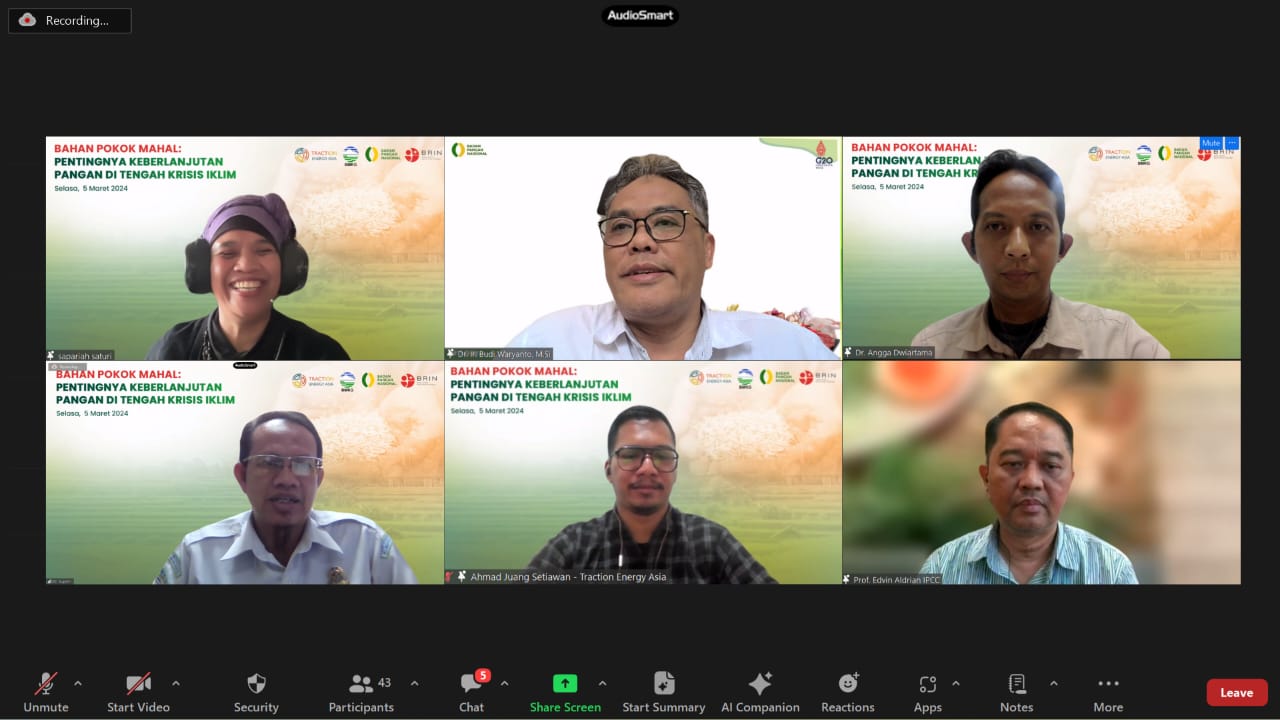
Selain itu, Bapanas juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan percepatan tanam di semester II tahun 2024 dimana telah diprediksi bahwa fenomena La Nina akan terjadi dan menyebabkan kondisi iklim lebih basah untuk pertumbuhan padi.
Ancaman atas produktivitas kelapa sawit dan perlunya diversifikasi sistem pertanian Sementara itu, Ahmad Juang Setiawan, Climate Researcher dari Traction Energy Asia mengungkapkan permasalahan iklim juga menjadi ancaman atas produktivitas kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng.
Ia mengatakan dampak krisis iklim seperti banjir, kekeringan, asap KARHUTLA (kebakaran hutan dan lahan), mempengaruhi produktivitas kelapa sawit melalui beberapa hal seperti pergeseran musim panen, menurunnya kualitas, rusaknya tanaman, hingga potensi kematian tanaman.
Hal lainnya yang berpotensi mengganggu ketersediaan minyak goreng adalah penggunaan kelapa sawit untuk biodiesel. Semakin tinggi tingkat pencampuran biodiesel, ketersediaan minyak goreng berpotensi akan menurun.
Secara umum stok minyak goreng terancam oleh dua hal, yaitu krisis iklim yang mempengaruhi produktivitas kelapa sawit, dan biodiesel yang mempengaruhi jatah minyak sawit untuk diolah menjadi minyak goreng. Juang mengatakan dalam 4 tahun terakhir, terjadi peningkatan konsumsi minyak goreng saat menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri sebesar rata-rata 38%.
Namun, jika ditelusuri lebih lanjut, kebutuhan akan energi lambat namun mengalami peningkatan. Pada bulan Agustus 2023, alokasi CPO untuk energi sudah melebihi alokasi untuk pangan, yaitu melebihi 1 juta ton sementara pangan dibawah 1 juta ton.
Hal ini seiringan dengan regulasi pemerintah untuk meningkatkan produksi biosolar, yang juga dikenal sebagai program pencampuran Bahan Bakar Nabati (B35). Menurutnya terdapat peluang besar dalam memanfaatkan minyak jelantah (Used Cooking Oils) sebagai bahan baku komplementer biodiesel.
Pengumpulan dan pengelolaan UCO sebagai biodiesel dapat menyelesaikan dua masalah lain yaitu masalah kesehatan dan lingkungan. Minyak jelantah berdampak negatif jika digunakan secara berulang, dan berdampak buruk pada lingkungan jika dibuang sembarangan. Juang juga menambahkan salah satu caranya untuk menuju pangan yang berkelanjutan adalah dengan melihat kembali kearifan lokal yang telah dikembangkan oleh petani-petani kecil di daerah yang sudah mempunyai mekanisme adaptasi perubahan iklim.
Ia mencontohkan seperti yang dilakukan pada masyarakat adat di Kasepuhan, Banten Selatan yang memiliki berbagai jenis varietas padi yang sudah disesuaikan dengan berbagai musim. Selain itu, mereka juga memiliki sistem prediksi awal musim tanam yang cukup baik untuk yang tingkat akurasinya bahkan bisa menyaingi model prediksi kontemporer (berbasis ENSO, suhu muka laut) pada daerah mereka sendiri.
Menurutnya hal ini penting untuk memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi sistem pertanian dibanding menggunakan menggunakan satu sistem yang sama untuk semua daerah.
“Pada kenyataannya, setiap daerah memiliki keunikan dan kebutuhan tersendiri yang harus dipertimbangkan,” tambahnya.
Perlunya pengelolaan pangan yang berkelanjutan Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2015 hingga tahun 2017, produksi padi meningkat dari 69 juta ton ke 81 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Namun sejak tahun 2018, produksi padi menurun cukup drastis, di angka 56,54 juta ton di 2018 hingga titik terendah di tahun 2023 sebesar 53,63 juta ton.
Faktor lain yang menyebabkan menurunnya produksi padi selain perubahan iklim yang ekstrem adalah karena berkurangnya luasan lahan sawah yang dipicu oleh alih fungsi lahan. Merujuk pada data tersebut, Dosen dan Peneliti Pangan di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, Angga Dwiartama khawatir karena sistem pangan kita, khususnya padi, sangat ringkih terhadap guncangan seperti El Niño.
Mengingat El Niño sebagai sebuah siklus iklim, dan bila dikaitkan dengan fenomena perubahan iklim ke depan, mungkin terjadi El Niño dan La Nina dengan potensi intensitas yang lebih besar. Menurutnya, berpikir secara ‘business as usual’ dalam produksi pangan harus ditinggalkan demi upaya mengantisipasi krisis iklim dan beralih ke arah keberlanjutan pangan.
Ia mengungkapkan tiga rekomendasi utama untuk adaptasi perubahan iklim dalam sektor pertanian padi. Pertama, pemerintah harus membangun infrastruktur lokal yang sesuai dengan karakteristik sosio-ekologis setiap wilayah.
Sentralisasi produksi pertanian harus dihindari, dan infrastruktur yang tangguh harus dibangun sesuai dengan sistem ekologis-sosial setempat. Kedua, dengan mayoritas petani padi Indonesia termasuk dalam kategori petani gurem yang rentan terhadap guncangan, pemerintah harus meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya pertanian yang mencukupi, seperti lahan, air, dan sarana produksi.
Ketiga, penguatan kapasitas masyarakat pedesaan secara luas melalui praktik adaptasi perubahan iklim juga penting. “Masyarakat pedesaan tidak hanya tentang pertanian, dan pemahaman yang lebih luas tentang strategi penghidupan dan praktik adaptasi perubahan iklim di pedesaan dapat memperkuat ketangguhan masyarakat terhadap perubahan iklim,” tuturnya.
Proyeksi Iklim di tahun 2024 Menurut Supari, El Niño diprediksi akan berakhir pada April tahun 2024, dan kemudian ada indikasi munculnya La Nina pada semester kedua 2024. “Tahun 2024 terdapat indikasi awal bahwa akan datang fenomena La Nina yaitu mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur,” ujarnya.
Lebih lanjut, Supari mengatakan bahwa selama 10 tahun terakhir kita lebih sering menghadapi iklim ekstrem baik itu El Niño, La Nina maupun IOD. Hanya di tahun 2016 yang kondisi iklim globalnya netral saat Indonesia mengalami musim kemarau.
Jika La Nina benar akan hadir pada tahun 2024, maka musim kemarau akan terjadi dengan sifat lebih basah. Hal ini akan baik untuk tanaman padi karena air tercukup, namun mungkin tidak cukup baik untuk tanaman hortikultura seperti sayuran dan cabai karena curah hujan yang berlebihan.
Ia menegaskan pentingnya untuk memahami informasi iklim ekstrem untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Pemerintah perlu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai literasi iklim, khususnya bagi para petani yang sebagian besar terdiri dari generasi muda. “Sehingga mereka melek teknologi informasi dan itu merupakan peluang untuk memberikan pemahaman pada setiap petani untuk mengurangi dampak risiko iklim ekstrem,” ungkapnya
Prof Edvin menambahkan kondisi Indonesia diuntungkan karena berada pada posisi adanya aliran samudra Pasifik menuju samudera Hindia, yang dikenal dengan aliran throughflow dimana aliran ini menjadi sinyal laut yang penting untuk memprediksi El Niño pada enam bulan kedepan dengan bantuan pemodelan laut.
“Dengan memanfaatkan sinyal di laut ini Indonesia dapat memprediksi kedatangan ENSO (anomali suhu permukaan laut di samudra pasifik), baik itu El Nino maupun La Nina yang dapat dimanfaatkan untuk kesiapan pangan dan antisipasi bencana kekeringan terutama bahaya kebakaran hutan,” tutupnya.










