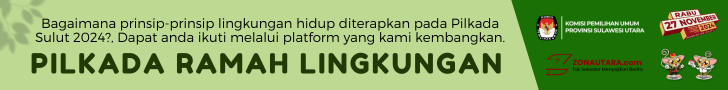Penulis: Ardiantiono, University of Kent
Keanekaragaman hayati dunia menurun drastis dalam beberapa dekade terakhir. Laporan terbaru Living Planet Index menunjukkan bahwa populasi satwa liar berkurang hingga 69% sepanjang rentang periode 1970 sampai 2018. Kondisi ini membuat pelaksanaan upaya-upaya konservasi semakin mendesak.
Sebagai negara megabiodiversitas, Indonesia menjadi salah satu pusat krisis biodiversitas akibat tingginya tingkat kehilangan spesies dan habitat. Sayangnya, perhatian terhadap isu ini masih belum sebesar isu deforestasi atau perubahan iklim.
Pada akhir 2022, Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) disepakati sebagai langkah global melindungi biodiversitas, dengan salah satu target ambius melindungi 30% luas daratan dan laut pada tahun 2030 (30×30). Indonesia yang turut mengadopsi kesepakatan ini perlu segera mengambil langkah konkret untuk mewujudkannya.
Kondisi hari ini – tantangan konservasi biodiversitas
Indonesia berada di peringkat kedua dunia dalam hal nilai biodiversitas dan nomor wahid untuk keanekaragaman spesies endemik.
Sekitar 63% wilayah daratan Indonesia masih berupa hutan (~120 juta hektare), tapi hanya 18% diantaranya (22,1 juta hektare) yang berstatus kawasan konservasi.
Meski memiliki kekayaan alam luar biasa, Indonesia menghadapi ancaman serius seperti deforestasi, perdagangan satwa ilegal, dan perubahan iklim.
Sebagai contoh, Indonesia kehilangan 9,79 juta hektare hutan primer antara 2001-2019, terutama akibat alih fungsi lahan untuk perkebunan, pertanian, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, Indonesia menjadi pusat perdagangan satwa liar ilegal dengan kerugian mencapai Rp 8.7 triliun per tahun. Di sektor kelautan, aktivitas pencurian ikan mengakibatkan kerugian sebesar Rp 290 triliun setiap tahunnya.
Perubahan iklim memperburuk situasi. Kebakaran hutan besar pada 2015 akibat fenomena El-Nino ekstrem membakar 4,6 juta hektare hutan. Ini adalah salah satu bencana lingkungan terbesar yang pernah terjadi. Dampaknya meluas hingga mengganggu kesehatan 40 juta orang di Indonesia dan negara tetangga.
Sayangnya, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan masih lemah. Dari 6.143 pengaduan yang diterima Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2015-2021, hanya 2.185 yang mendapat sanksi administratif. Sanksi tersebut sering kali tidak memberikan efek jera. Bahkan, banyak perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan lolos dari hukuman.
Keterbatasan pendanaan juga menjadi hambatan besar dalam mencapai target nasional maupun internasional seperti target 30×30 GBF. Untuk mencapai 14 target nasional dalam Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2025-2045, Indonesia membutuhkan setidaknya Rp75,53 triliun per tahun. Namun, realisasi pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 terkait biodiversitas baru mencapai Rp 9,85 triliun atau hanya sekitar 13% dari kebutuhan tersebut.
Di samping itu, kapasitas untuk memantau status biodiversitas juga masih terbatas, sehingga menyebabkan kebijakan konservasi sering kali tidak berbasis pada data ilmiah yang memadai.
Melihat kondisi di atas, pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang sepertinya akan menghadapi tantangan besar dalam mencapai target konservasi dan komitmen internasional seperti Pakta Kunming-Montreal.
Catatan penting untuk Prabowo
Misi pemerintahan Prabowo-Gibran lebih menekankan pada penguatan ekonomi dan ketahanan nasional. Meski demikian, perlindungan biodiversitas tetap menjadi bagian dari program ekonomi hijau mereka.
Prabowo juga berencana membentuk badan khusus pengendalian perubahan iklim yang menunjukkan adanya perhatian terhadap isu iklim dan biodiversitas di masa mendatang.
Namun, beberapa catatan penting perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa agenda pembangunan dapat berjalan selaras dengan konservasi alam.
Misalnya, ambisi Prabowo menjadikan Indonesia sebagai pemimpin energi hijau. Pengembangan energi hijau melalui perluasan hutan tanaman energi dan perkebunan sawit berisiko meningkatkan deforestasi jika tidak direncanakan dengan matang.
Pemerintah perlu memastikan bahwa ekspansi energi hijau tidak memanfaatkan kawasan hutan, apalagi area bernilai konservasi tinggi.
Selain itu, UU No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang baru-baru ini disahkan telah memberikan pijakan hukum yang lebih kuat dengan memperketat sanksi dan membuka jalan bagi pendanaan swasta. Namun, penting bagi pemerintah untuk menghindari sentralisasi penetapan kawasan konservasi yang berpotensi mengabaikan hak masyarakat adat dan lokal.
Pemerintah perlu menciptakan sistem konservasi yang lebih inklusif dengan mengakui peran masyarakat yang menjadi garda terdepan dalam upaya konservasi.
Kebebasan akademik dan transparansi data menjadi kunci
Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mendorong keterbukaan informasi dan kebebasan akademik agar kebijakan konservasi berbasis bukti ilmiah yang kuat.
Transparansi data sangat penting untuk mengetahui status biodiversitas secara akurat dan mengukur pencapaian target lingkungan. Tanpa data yang jelas, kebijakan seperti kapal tanpa kompas, terombang-ambing tanpa arah.
Prabowo tidak boleh mengulang perilaku represi antisains yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Tanpa kebebasan akademik, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui kondisi biodiversitas yang sesungguhnya?
Dengan mendorong budaya keterbukaan dan bekerja sama dengan komunitas ilmiah, pemerintah dapat membangun fondasi konservasi yang kuat dan berbasis sains, menjamin keberlanjutan biodiversitas Indonesia.
Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki peluang besar untuk memulai berbagai langkah strategis dalam konservasi biodiversitas sejak awal masa jabatan mereka. Dengan memanfaatkan momentum ini, pemerintah dapat menunjukkan komitmen nyata dan keberanian untuk memprioritaskan kepentingan ekologis jangka panjang.
Kolaborasi lintas sektor perlu diperkuat agar upaya konservasi berjalan efektif, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan sehingga tercipta sinergi yang menghasilkan manfaat nyata bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Ardiantiono, PhD Student, University of Kent
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.