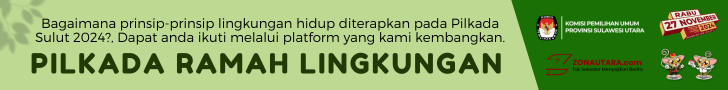Oleh: Anggi M. Lubis, The ConversationPekan lalu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) membakar pakaian bekas impor senilai Rp 9 miliar di Karawang, Jawa Barat, dalam rangka penegakan hukum terkait larangan impor pakaian bekas.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa aturan ini adalah untuk melindungi industri tekstil Indonesia yang dirugikan oleh pakaian impor bekas yang dijual dengan harga murah. Akibatnya, masyarakat lebih memilih pakaian bekas impor ketimbang produk lokal.
Kemendag juga mengklaim bahwa larangan ini terkait dengan alasan kesehatan. Tes laboratorium menunjukkan bahwa pakaian bekas mengandung jamur yang berbahaya untuk kesehatan kulit meski pun sudah dicuci berulang kali.
Hal ini menimbulkan dilema tersendiri. Pasalnya, hal ini bisa menggoyang bisnis thrift shop yang umumnya menjual pakaian bekas bermerek dengan harga terjangkau dan menjadi pilihan yang digemari kawula muda untuk berbelanja. Banyak di antara toko-toko daring maupun luring yang berkecimpung di pasar thrift shop merupakan usaha kecil.
Larangan impor baju bekas ini bak pedang bermata dua. Namun, di satu sisi, perdebatan ini bisa jadi pemantik atas kesadaran untuk mengembangkan merek lokal dan membuat konsumen bangga dengan barang produksi dalam negeri.
Impor baju bekas: dibolehkan atau dilarang?
Dua pakar yang diwawancarai The Conversation memiliki dua pandangan berbeda mengenai perlunya larangan baju impor ini.
Hasran dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) berpandapat larangan impor baju bekas ini sudah tepat. Selain karena terbukti mengandung jamur kapang yang mengancam kesehatan, keberadaan pakaian bekas impor juga mengancam industri tekstil dalam negeri yang sedang dalam kondisi pemulihan akibat pandemi dan kenaikan bahan baku.
“Pelarangan impor pakaian bekas ini diperlukan karena industri tekstil dalam negeri akan kalah bersaing mengingat harga pakaian bekas yang impor ini tentunya lebih murah. Memang ini akan sangat berdampak bagi usaha thrift shop, tapi jika tidak diatur impornya justru dampak negatif yang lebih besar justru akan dirasakan oleh industri tekstil tanah air,” ujarnya.
Hasran mengungkapkan bahwa 80% produsen pakaian di Indonesia didominasi oleh industri kecil dan mikro dan impor pakaian bekas selama ini memangkas pangsa pasar mereka sebesar 12%-15%.
“Bayangkan saja, pakaian yang seharusnya harga ratusan ribu dijual dengan rentang harga Rp 50.000-an. Jelas ini jadi pukulan telak bagi industri tekstil dalam negeri karena tidak bisa bersaing dari segi harga,” terangnya.
Sementara, Adinda Tenriangke Muchtar dari The Indonesian Institute, justru berpendapat bahwa impor baju bekas tidak perlu dilarang karena mengancam penghidupan thrift shop yang kebanyakan adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sudah beroperasi sejak lama, seperti di Pasar Senen, Jakarta.
“Mengapa saya bilang seharusnya tidak perlu dilarang? Karena kita tau thrifting ini sudah ada sejak lama dan menghidupi pedagang kecil kita yang ada di Senen, bahkan di daerah-daerah termasuk di Medan dan di Nias (Sumatera Utara),” ujarnya.
Aturan ini bahkan sebetulnya sudah ada sejak 2015 dan terbukti tidak efektif. Penjualan baju impor, menurut Adinda, bisa dibilang bukanlah pasar gelap karena memang tetap dibiarkan menjamur dan memiliki pasarnya sendiri.
Memang, Kemendag tidak terang-terangan melarang penjualan baju impor bekas yang beredar di pasaran. Kementerian hanya menegaskan bahwa “impornya saja yang dilarang”.
Menurut Adinda, pasar seharusnya tetap ada tanpa intervensi pemerintah. Yang terpenting adalah melakukan penegakan hukum terhadap pakaian bekas impor itu sendiri, misalnya melalui pengecekan di bea cukai dan dengan menuntut tanggung jawab penjual untuk menanggulangi persoalan isu kesehatan. Apalagi, tidak ada jaminan bahwa baju bekas produksi dalam negeri bebas dari masalah kesehatan.
“Yang perlu didorong juga adalah pedagang yang bertanggung jawab. Artinya, ketika dia menerima barang bekas, seyogyanya, misalnya, dia ikut mencuci pakaian itu […] bukan hanya menjual dari gudang, dari pelabuhan, itu langsung dijual begitu aja,” tegasnya.
Selain itu, Adinda juga menambahkan bahwa aturan ini membatasi kebebasan konsumen untuk memilih. Utamanya, terhadap konsumen muda yang memang mengejar baju bermerek dengan harga terjangkau. Ada baiknya pasar tetap dibiarkan, dengan memberikan edukasi ke konsumen mengenai konsekuensi pembelian baju bekas impor.
Kebanggaan terhadap produk lokal perlu diperkuat
Terlepas dari penolakannya terhadap larangan impor baju bekas, Adinda menegaskan bahwa Indonesia sebetulnya punya potensi besar dalam mengembangkan merek lokal berkualitas. Kini, banyak anak muda yang bangga menggunakan brand dalam negeri.
“Ini kan trend ya. Ada gaya hidup, ada preferensi pilihan. Tapi jangan khawatir, kita juga tau produk2 lokal yang baik dari Bandung, dari Jogja, dari Bogor, Bali, dan sebagainya, itu juga punya pasarnya sendiri,” terangnya.
Adinda menilai, merek lokal kini tidak kalah kompetitif.
Sejumlah brand asal Indonesia kini telah mendunia. Bahkan, elit politik, termasuk Presiden Joko Widodo, kerap mengenakan produk lokal dalam sejumlah acara.
Sebut saja merek Eiger, Cotton Ink, Erigo Apparel, Major Minor, Minimal, dan NAH Project.
Terkait hal ini, Hasran dan Adinda punya resep untuk meningkatkan daya saing produk lokal di tengah gempuran produk impor.
Pertama, memperbaiki kualitas bahan baku.
Menurut Hasran, jika bahan baku tekstil murah dan mudah diperoleh, industri dalam negeri dapat membuat produk yang berkualitas dengan harga lebih terjangkau. “Jika memang harus impor bahan baku maka pemerintah perlu mempermudah proses perizinannya,” ujarnya.
Kedua, dukungan teknis seperti modal, pengembangan perencanaan bisnis, literasi digital, dan literasi keuangan – mengingat kebanyakan merek lokal dikembangkan oleh pelaku UMKM.
Perkara modal, Adinda berargumen bahwa hal ini bisa dilakukan dengan pemberian pinjaman atau dukungan pemerintah untuk mempertemukan pelaku UMKM fesyen lokal dengan investor.
Sementara, Hasran menekankan pentingnya keterampilan digital.
“Kemampuan digital ini akan memperbaiki cara desain dan juga marketing menjadi lebih menarik bagi para kawula muda. Pemerintah perlu menggencarkan program pelatihan digital bagi para pelaku di industri tekstil ini,” ujarnya.
Ketiga, pembukaan akses pasar.
Menurut Adinda, hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pameran atau bazaar dengan sewa tempat yang lebih murah, seperti melalui Pekan Raya Jakarta (PRJ), yang dilaksanakan tahunan untuk merayakan ulang tahun Jakarta dan ramai mengundang pengunjung.
Pembukaan pasar juga bisa dilakukan lewat inisiatif mall untuk menyediakan ruang bagi brand lokal baik dalam bentuk toko maupun pameran.
Melihat animo masyarakat yang sebetulnya cukup baik terhadap brand lokal, Adinda berkata, “Jadi saya sih sebenernya percaya, biarkan market itu tumbuh dan berkembang dengan natural. Tidak terlalu banyak intervensi dan justru didorong support yang sifatnya konstruktif dan tidak menutup kompetisi seperti melakukan pelarangan-pelarangan impor, termasuk barang-barang bekas.”![]()
Anggi M. Lubis, Editor Bisnis + Ekonomi, The Conversation
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.