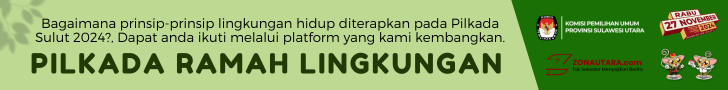Oleh: Taufik Rachmat Nugraha, Universitas Padjadjaran
Beberapa tahun ke belakang, pemerintah tampak serius menggenjot mutu perguruan tinggi agar setara dengan kampus terkemuka dunia. Salah satunya adalah memperbanyak publikasi di “jurnal internasional bereputasi”, yang seringkali dimaknai sebagai jurnal terindeks Scopus – basis data pustaka komersial yang populer di dunia akademik – agar perguruan tinggi dalam negeri dapat naik peringkat secara global.
Pada 2023, misalnya, hanya ada lima perguruan tinggi Indonesia yang masuk top 500 dalam daftar peringkat Quacquarelli Symonds(QS) yang jadi rujukan pemerintah. Dua dari enam bobot terbesar dalam penilaiannya berhubungan langsung dengan publikasi, yakni reputasi akademik dan sitasi per fakultas.
Selain sebagai indikator pemeringkatan perguruan tinggi, penerbitan di jurnal bereputasi pun terikat dengan proses promosi jabatan dosen di Indonesia.
Di satu sisi, semangat publikasi ini bisa baik untuk mendorong kualitas akademisi di Indonesia, dari membuat dosen lebih terbiasa menulis hingga mendorong mereka berkontribusi membangun wawasan keilmuan di tingkat global.
Berdasarkan kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), selama 2017-2021 ada kenaikan artikel ilmiah yang terbit di jurnal-jurnal Scopus yakni sebanyak 7%-13% tergantung kategori peringkat jurnalnya (Q1 hingga Q4). Ini berarti kebijakan publikasi di Indonesia mulai menulai hasil positif – setidaknya secara kuantitas.
Sayangnya, kebijakan ini justru menjadi bumerang ketika sebagian kalangan akademisi justru mencari jalan pintas untuk penerbitan.
Meski belum ada riset yang melakukan pemetaan, sebagai mantan anggota unit publikasi di fakultas saya pada periode 2021-2022 dengan pengalaman juga sebagai direktur pelaksana di suatu jurnal nasional selama 2020-2021, saya menyaksikan munculnya banyak praktik “pencaloan” publikasi melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi.
Banyaknya akademisi, termasuk mahasiswa S3 di Indonesia yang belum paham kaidah penulisan riset dan budaya publikasi di tengah “paksaan” penerbitan karya ilmiah, memberi ruang hadirnya praktik dan oknum tak bertanggung jawab. Mereka menawarkan jasa menjadi penghubung penulis dan jurnal dengan janji penerbitan secara instan.
Mencari jalan pintas
Penerbitan di jurnal yang bereputasi dan berkualitas tinggi umumnya memerlukan kualitas riset di atas rata-rata dengan proses reviu sejawat (peer review) yang ketat dan memakan waktu lama.
Praktik pencaloan memungkinkan pemangkasan waktu tunggu publikasi bagi dosen yang memerlukan kenaikan pangkat, atau bagi mahasiswa doktoral yang mengejar kelulusan, dari hitungan bulan atau tahun menjadi hitungan sekian minggu saja. Bahkan, para calo juga menawarkan jaminan terbit pada jurnal dengan peringkat atau nilai Q yang dikehendaki.
Pelakunya bisa bervariasi: ada yang oknum dosen, ada yang individu, dan ada juga yang “difasilitasi” kampus baik secara terang-terangan maupun tidak.
Tentu saja publikasi lewat calo tidak gratis. Dalam pengamatan saya, dosen harus merogoh ongkos yang cukup tinggi, antara Rp 5-30 juta. Padahal, lebih dari 80% jurnal yang terindeks di Scopus itu biayanya dibebankan kepada pembaca (akses artikelnya berbayar) sehingga para penulis tidak dibebankan biaya pengajuan atau penerbitan naskah.

(Ilustrasi oleh Taufik Rachmat Nugraha), Author provided
Bahayanya juga, publikasi lewat jalur calo seringkali merujuk pada jurnal-jurnal yang cenderung tidak aman.
Ini termasuk jurnal-jurnal yang terindikasi bersifat “predator”. Umumnya mereka meminta bayaran tinggi dari akademisi tapi memiliki proses reviu ilmiah yang lemah atau bahkan nihil.
Jurnal Humanities and Social Sciences Review (HSSR) pada 2019 tiba-tiba meraih kuartil Q1 (kategori peringkat tertinggi) di Scopus. Namun, pada tahun yang sama, jurnal ini sepenuhnya dikeluarkan dari indeks tersebut karena masalah etika dan standar publikasi. Ini berujung membuat sebagian dosen di Indonesia kecewa dan merugi telah membayar uang hingga jutaan rupiah.
Beberapa peneliti pun menemukan puluhan hingga potensi ratusan jurnal terindeks Scopus yang terindikasi bersifat predator.
Ini bisa saja dimanfaatkan oleh para calo publikasi karena proses skrining editorialnya yang lemah, dan memakan korban banyak akademisi Indonesia.
Bahkan, para calo umumnya hanya meminta manuskrip yang sesuai dengan struktur Pendahuluan, Metode, Hasil, dan Pembahasan (Introduction, Method, Results, Discussion atau IMRaD) dengan reviu yang seringkali tak berhubungan dengan substansi naskah.
Suatu studi tahun 2021 dari tim peneliti Charles Uiversity di Praha, Republik Ceko yang menggegerkan dan memicu perdebatan di dunia akademik menemukan Indonesia adalah negara kedua terbanyak penghasil karya ilmiah di jurnal terindikasi predator yang terindeks Scopus selama periode 2015-2017 – yakni 17% atau setiap 1 dari 6 artikel yang terbit.
Yang paling apes adalah ketika calo merujuk pada jurnal-jurnal bajakan atau kloning, yang didesain mirip sekali dengan jurnal bereputasi yang asli atau bahkan adalah hasil peretasan.
Bagi akademisi yang terkelabui, tulisan mereka pada jurnal tersebut bisa jadi tak terekam di indeks Scopus – atau terekam namun tidak bisa ditelusuri keberadaan dokumennya – sehingga tidak akan diakui oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti). Bagi mahasiswa doktoral, ini bisa berarti mereka terancam gagal mengikuti sidang disertasi.
Resep kekacauan
Dalam pandangan saya, fenomena munculnya para calo publikasi ini adalah akibat kombinasi tiga faktor:
- Kebijakan publikasi oleh pemerintah yang implementasinya sangat berfokus pada menggenjot kuantitas
- Pengetahuan di kalangan akademisi dan mahasiswa doktoral yang masih cenderung lemah akan standar, budaya, dan norma publikasi ilmiah yang baik
- Tekanan akademik terhadap mahasiswa doktoral dan akademisi yang besar untuk melakukan publikasi pada jurnal bereputasi tanpa disertai pendampingan.
Niat pemerintah menaikkan mutu pendidikan tinggi perlu dibarengi kebijakan yang memadai dan berorientasi pada insan akademik – termasuk memperhatikan beban kerja mereka yang besar meliputi mengajar hingga mengurus administrasi berbelit – bukan yang sekadar berorientasi pada pemeringkatan.
Semangat yang saat ini ada justru menimbulkan budaya jalan pintas dalam dunia akademik.
Jika praktik seperti pencaloan publikasi tidak segera diberantas, reputasi akademisi Indonesia menjadi taruhannya.

(Ilustrasi oleh Taufik Rachmat Nugraha), Author provided
Untuk menguranginya, pemerintah dan perguruan tinggi dapat mengubah skema kewajiban publikasi bagi mahasiswa doktoral bukan sebagai penentu kelulusan, namun sebagai poin tambahan atau misalnya untuk meraih predikat cum laude.
Dengan begitu, mahasiswa doktoral bisa fokus sepenuhnya untuk menyelesaikan kuliah dan menyempurnakan risetnya tanpa dihantui tekanan publikasi di “jurnal internasional bereputasi”.
Selain itu, pemerintah dan perguruan tinggi juga harus lebih menggalakkan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan terkait publikasi pada jurnal-jurnal bereputasi sebagaimana yang diminta dalam pedoman Penilaian Angka Kredit Dosen (PO-PAK) keluaran Dikti. Membiarkan banyaknya dosen dan periset yang belum terbiasa dengan hal ini sama saja membiarkan lahan subur tumbuhnya para calo.![]()
Taufik Rachmat Nugraha, Research Fellow at The Indonesian Centre for the Law of the Sea (ICLOS), Universitas Padjadjaran
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.