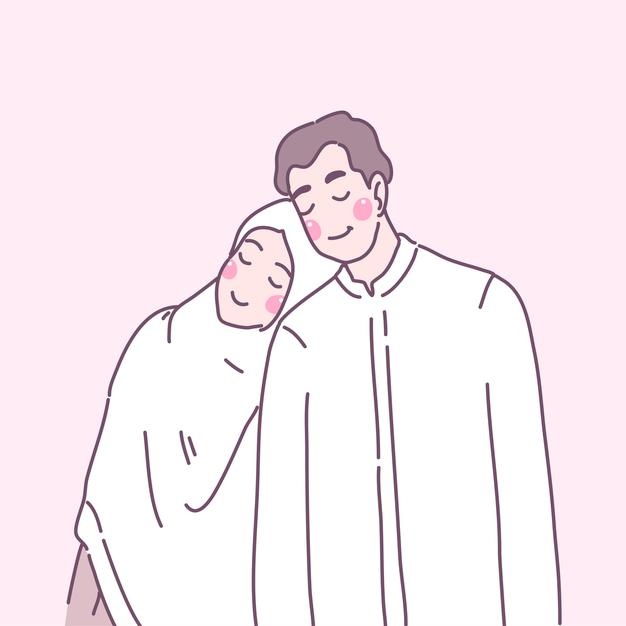“Kapan bawa calon suami kamu ke rumah, Ndah?”
Gadis bertubuh mungil itu melengos dan memilih menghindar saat diserang oleh Helmi, ibunya, dengan pertanyaan yang hampir setiap hari dilontarkan ketika ia pulang kerja. Seperti sekarang ini, dia sengaja tidak menjawab dan langsung masuk ke kamarnya dan menutup pintu.
Sebenarnya bukan ingin bersikap kurang ajar, tapi dia sendiri sudah lelah dengan segala aktivitas pekerjaannya di kantor. Lagi pula perasaan dia tadi mengucapkan salam? Bukannya dijawab ‘waalaikumsalam’ malah ditanya calon suami. Andai kekasih itu bisa dibeli, mungkin sekarang sudah berlusinan koleksi pacar dimiliki.
Indah menaruh tas di atas meja samping tempat tidur. Selesai mandi, dia ingin segera melanjutkan novel yang sedang digarapnya. Lima hari lagi deadline dan dia masih butuh empat puluh halaman untuk menamatkan naskah tersebut.
Ironi, dia dikenal sebagai penulis novel romantis yang selalu happy ending. Tapi kisah cintanya justru sering sad ending. Hidup memang tak seindah cerita romantis dalam fiksi. Gadis yang mengenakan jilbab biru tosca itu menatap dirinya di cermin dengan senyum kecut. Ia teringat sebuah ungkapan.
Seseorang diberi sesuai kualitas niatnya.
Mungkin selama ini dirinya kurang niat dalam ikhtiar mencari calon suami. Terbukti ia belum dipertemukan dengan pria yang akan menjadi suaminya.
“Kamu tuh, ya, kalo Mama lagi ngomong, ya didengerin dulu!” Dari ruang tengah terdengar suara Bu Helmi—wanita yang sudah delapan tahun dipercayakan oleh Kepala Desa menjabat sebagai Ketua RT di kampung ini—mulai meninggi. Terkadang Indah merasa ibunya memang pantas menjabat sebagai perangkat desa karena kecerewetannya.
“Indah dengar, kok, Ma. Besok saja mampir ke supermarketnya, ya?” jawab Indah asal.
Tiba-tiba pintu kamar terbuka sedikit, hanya bagian kepala ibunya yang terlihat dengan tampang sarkastis. “Ngapain ke sana? Jangan lupa jemput Mama dulu.”
Indah tersenyum simpul lalu menaikkan bahunya. “Mau ngecek, siapa tahu ada calon menantu Mama dijual di sana.”
Ibu Helmi mendorong daun pintu dengan kasar hingga terbuka lebar, kemudian bersedekap dan bersandar di dinding kamar. “Indah, Mama enggak sedang bercanda. Ingat, umur kamu sekarang sudah 28 tahun. Mama enggak mau kamu enggak nikah-nikah sampai dikata perawan tua,” ketusnya sambil menggelengkan kepala. “Mama saja dulu melahirkan kamu saat Mama berumur 18 tahun, loh.”
Indah tersenyum sambil bergerak mendekati lalu menggenggam tangan ibunya. “Mama tahu, kan, surat Adz Dzariyat ayat 49? Di situ tertulis, ‘dan segala sesuatu Kami ciptakan kamu berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah’. Janji Allah itu benar, Ma. Dan Allah telah menjanjikan bahwa tiap orang pasti menikah. Hanya masalah waktu dan ikhtiar saja.”
Tanpa ekspresi Ibu Helmi mengusap kepala putrinya dan berkata, “Dan, kamu pasti tahu juga, ada ayat yang mengatakan ‘sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan [yang ditakdirkan pada] suatu kaum sebelum mereka [berusaha] mengubah keadaan [yang ditakdirkan pada] diri mereka sendiri.”
“Iya, Mama. Indah paham,” Merasa pegal berdiri, Indah duduk di tepi ranjang kemudian melepas sepatu lalu jilbab di kepalanya. Rambut hitam pekat terkucir kini terlihat. “Tapi… Indah enggak bisa menikah sebelum ketemu Papa.”
Masih berdiri dekat pintu Ibu Helmi bergeming. Tidak lagi menatap putrinya yang kini tertunduk. Hatinya sakit sekaligus merasa bersalah karena ia melahirkan Indah tanpa kehadiran sosok ayah. Pernikahan yang tak direstui memang tidak akan bertahan lama.
“Indah butuh Papa untuk jadi wali dan menikahkan Indah nanti, Ma.”
“Terserah. Tapi asal kamu tahu, lelaki yang ingin kamu temui itu adalah orang yang enggak pernah peduli sama keberadaan kamu,” geram ibu Helmi, “pokoknya, kalau sampai bulan depan enggak ada laki-laki datang melamar kamu, Mama yang akan mencarikan jodoh untuk kamu, dengan pria pilihan Mama!”
Kemudian Ibu Helmi melangkah keluar dan menutup pintu kamar dengan cukup keras.
***
Gadis bermata sayu yang tadinya ceria, kini berubah cemberut setelah beberapa menit menatap layar berukuran 14 inci di atas meja kantornya. Sejenak ia bersandar di bahu kursi seraya menarik napas kemudian diembuskan secara berulang-ulang untuk menenangkan hatinya yang sedang galau.
“Ditolak lagi, Ndah?” tanya seseorang di belakangnya.
Indah tersentak kaget, ia mendongak dan mendapati Rian—teman sekaligus HRD di kantor—berdiri sambil memegang dua mug berisikan kopi susu.
“Astaghfirullah. Bapak kagetin saja, nih,” ucap Indah seraya mengusap dadanya yang hampir mau copot. Ia menggeleng. “Lebih tepatnya belum. Baru juga tiga minggu yang lalu saya mengirim naskahnya.”
“Pasti naskahmu bakal diterima, kok.”
“Aamiin. Terima kasih, Pak.”
Cowok bertubuh tegap itu tersenyum seraya duduk di sebuah kursi di sebelahnya lalu menyodorkan satu mug pada gadis itu. Dengan wajah semringah Indah menyambut lalu meminumnya.
“Kok tahu, sih, kalo saya lagi butuh ini?” Indah mengangkat mug di tangannya yang isinya tersisa setengah.
Pemuda tampan itu kembali tersenyum, kali ini dengan kilatan geli di matanya. “Kamu ke kantor terlalu pagi, Ndah. Ini baru jam 6.30… kantor buka jam 8. Udahbisa ketebak, kan, kamu ke sini tanpa sarapan dulu?”
“Iya, sih. Lagian Bapak juga kayaknya enggak pulang dari semalam. Lemburkah?” Indah memerhatikan pakaian pria itu masih sama dengan yang dipakainya kemarin. Kemeja biru dan celana hitam berbahan denim.
“Ya. Ada yang harus segera kuselesaikan,” ucap Rian pelan, kemudian menatap gadis itu dengan serius, “bisa enggak, kamu enggak usah manggil aku ‘Bapak’? Soalnya berasa aku ini udah tua banget. Apalagi dipanggil ‘Bapak’ sama orang yang bertubuh mungil seperti kamu. Padahal umur kita cuma berjarak dua tahunan, kan?”
Tanpa rasa canggung Indah tertawa keras. Lalu menggeleng. “Ini di kantor. Dan Bapak atasan saya. Lagian, siapa suruh punya badan tinggi besar, gitu?”
Walau Rian tampak kesal, namun bibirnya tetap menampilkan senyuman yang mungkin bisa membuat Indah meleleh, tapi gadis itu buru-buru mengenyahkan khayalannya itu dengan ber-istighfar.
Rian melihat gadis yang mengenakan jilbab pink itu nampak salah tingkah. Untuk menenangkan perempuan yang dicintainya dalam diam, ia mencoba mengalihkan suasana dengan bertanya, “Kamu pagi-pagi ke sini bukan karena nggak sabar ingin ngecek E-mail dari Penerbit saja, kan?”
“Memang bukan, sih. Saya buru-buru ke kantor biar enggak dicecar lagi soal jodoh.” Dia menarik napas. “Kemarin Mama sudah mewanti-wanti kalau minggu depan saya bakal dipertemukan dengan calon suami saya.”
“Dan, kamu dipaksa menerima perjodohan itu?”
Indah mengangguk, dengan tawa dipaksakan. “Tadinya saya berharap novel kelima saya terbit tahun ini. Tapi, sepertinya buku nikah yang bakal terbit duluan.”
Lelaki murah senyum itu mengangguk menenangkan meski di hatinya terasa pahit. “Sebagai atasan, aku hanya bisa bilang, kamu harus yakin bahwa setiap kejadian sekecil apa pun itu pasti sudah diatur dan seizin Allah,” Rian tersenyum lembut, “dan… sebagai teman, aku ikut bahagia kalau kamu bahagia.”
Indah terenyuh. Entah kenapa ia merasa ada sesuatu yang baru saja hilang dalam hatinya, tapi apa?
***
Pukul 02.45 dini hari. Indah belum juga dihinggapi rasa kantuk. Sejak percakapannya dengan Rian beberapa hari lalu telah menyadarkan bahwa dia mencintai pria itu. Dan Indah hanya mampu memendam rasa tanpa harus diutarakan. Akhirnya ia memutuskan salat Istikharah.
“Ya Allah, sekiranya Engkau tahu bahwa urusan ini lebih baik untuk diriku, agamaku, dan kehidupanku, serta [lebih baik pula] akibatnya [di dunia dan akhirat], maka takdirkanlah dan mudahkanlah urusan ini bagiku, kemudian berkahilah aku dalam urusan ini… dan takdirkanlah kebaikan untukku di mana pun, kemudian jadikanlah aku rida menerimanya.”
Dengan penuh kepasrahan dan segala pengharapan tentang jodohnya, gadis berparas manis itu menangis dalam doa.
***
Saat memasuki beranda rumahnya, Indah melihat sebuah mobil mewah terparkir di halaman. Tiba-tiba jantung perempuan mungil itu berdetak cepat. Dengan rasa penasaran ia terus berjalan meski kakinya terasa berat untuk bergerak.
“Assalamualaikum….”
“Waalaikumsalam….”
Gadis yang kini berdiri di depan pintu itu terkejut setelah melihat siapa yang menjadi tamunya. Ini seperti mimpi, tapi nyatanya dia tidak sedang bermimpi. Seorang pria paruh baya berkacamata seketika berdiri dan mendekati Indah. Lelaki itu tersenyum tapi tatapan matanya tampak sendu.
“Ini Papa, Nak. Maafkan Papa yang sudah pergi meninggalkamu dulu.” Tangan pria itu menyentuh kepala Indah yang masih mematung dengan bulir bening terus mengalir deras di pipinya. “Papa harus menunggu waktu yang tepat untuk menemuimu, Anakku.”
“Apa maksud Papa, nunggu waktu? Waktu apa? Dan kenapa harus selama itu?” tanya Indah. Ia menatap kedua orang tuanya secara bergantian.
“Papa enggak bisa menemuimu selama nenek kamu masih ada.” Pria itu menarik napas panjang lalu menatap putrinya dengan sayang. “Sekarang Papa bisa menemuimu kapan pun dan insya Allah Papa siap jadi wali pernikahanmu nanti.”
Tangisan haru gadis itu pecah dan langsung menghambur ke pelukan ayahnya. Sosok figur yang selama ini ia rindukan. Kemudian dia menoleh ke arah ibunya yang duduk memasang wajah datar. Melalui tatapan Indah bertanya. Mengapa Mama menerimanya? Bukankah selama ini Mama membenci Papa?
Seperti memahami tatapan itu, Helmi menjawab, “Mama terpaksa mengizinkannya ke sini supaya kamu enggak punya alasan lagi untuk enggak menikah,” ucap Helmi, “karena Mama sudah menentukan dan berencana kalau besok itu calon suami dan mertuamu bakal datang melamar kamu. Dan Mama nggak mau menerima penolakan kamu lagi!” tambahnya, lalu meninggalkan ruangan itu.
Indah hanya bisa menangis dalam pelukan Papa. Di satu sisi, dia bahagia akhirnya bisa bertemu dengan sang ayah kandung. Namun sisi lain, hatinya hancur karena ia akan kehilangan pria yang dicintai.
***
Setelah turun dari taksi online, Indah berhenti tepat di halaman depan rumahnya. Sebelum masuk ia harus menyiapkan diri serta menguatkan hatinya dulu untuk menerima perjodohan. Mata teduh gadis itu melihat beberapa mobil mewah terparkir di sana.
Samar terdengar percakapan diselingi tawa kecil dari dalam. Ya, sepertinya keluarga sang calon suami sudah datang. Dia memang pulang terlambat, selain karena pekerjaan menumpuk, ia juga ingin bertemu dengan Rian. Namun ternyata pria itu sudah resign dari kantornya karena ditarik oleh perusahaan lain dan mendapatkan promosi jabatan di tempat kerja barunya. Indah merasa kecewa sebab lelaki itu pergi tanpa berpamitan dengannya. Tapi, memangnya dia siapa?
Sebelum melangkah, ia menarik napas dalam lalu mengembuskan secara perlahan, sejenak dia memejamkan mata untuk menenangkan hatinya. Laa tahzan innallaha ma’anaa….
“Assalamualaikum, Ndah,” salam seorang di belakangnya.
Terperanjat, Indah berbalik badan seraya menjawab, “Waalaikumsalam… Bapak?”
Ternyata orang itu adalah Rian. Lelaki yang saat ini mengenakan kemeja putih dan celana berbahan hitam itu tersenyum sembari bergerak mendekat. Indah merasa hatinya berdegup kencang. Saking gugupnya tubuhnya sampai gemetar.
“Iya, ini aku, Rian. Bukan Bapak.” Kini pria tersebut berdiri tepat di depannya. “Aku datang untuk dua hal… pertama, aku mau ngasihini ke kamu. Buka!” ucapnya seraya menyodorkan sebuah amplop coklat padanya.
Gadis itu mengernyit, ia mengambil amplop berisikan sebuah kertas tersebut dan membukanya dengan rasa deg-degan. Setelah membaca saksama, refleks Indah melongo lalu menatap tak percaya pada pria di depannya. “Kamu seorang editor senior di sebuah penerbit besar itu?”
Rian tersenyum dan mengangguk mantap. “Iya, Ndah. Selama ini aku memang menggeluti dua pekerjaan. Dan, selamat. Naskahmu diterima di penerbitan tempatku bekerja.”
Tanpa permisi pria itu menarik lembut tangan Indah kemudian berjalan ke rumah. Sambil berkata, “Sekarang, temani aku untuk ketemu calon mertua.”
“Apaa? Apa maksudnya calon mertua?” Indah tercekat, namun dirinya tak bisa menghentikan langkahnya untuk terus mengikuti pria itu. “Lagian di dalam orang tuaku sedang menerima lamaran pria lain untukku, Rian.”
Mendengar pernyataan tersebut, bukannya berhenti, lelaki itu justru semakin menggenggam tangannya dan terus berjalan hingga tiba di depan orang-orang di dalam sana yang kini memandangi kami dengan tatapan terkejut.
“Kalian sudah saling kenal?” tanya Helmi yang seketika berubah jadi semringah. “Wah, Jeng! Sepertinya kita enggak perlu berusaha menjodohkan keduanya karena mereka kelihatannya memang sudah ditakdirkan berjodoh.”
Indah hampir tersedak ludahnya sendiri saat mendengar celetuk sang Mama. Lalu dia menatap tajam lelaki di sebelahnya yang kini tampak tersenyum penuh kemenangan.***
selesai